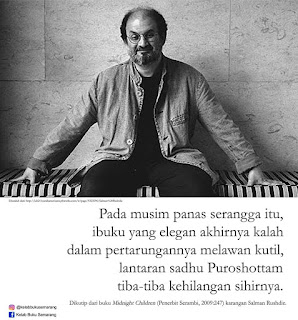Cuma tersisa cuilan telur bacem di dagumu
dan waktu masih berpikir berapa helaan
bisa direken untuk menyaksikan
yang kecil
mengering
dan jatuh
Jalanan sebentar lagi bakal membuka amarahnya
Mengembalikan lagi bau oli, dentang jam sebuah gereja,
matahari putih setengah delapan, juga rasa lapar
yang jadi sok tahu akan kemana
jika hendak
mengejar kita
Di samping pancuran (aku ragu apakah kelak
akan ada
di samping kiri atau di samping kanan)
yang piawai menarikan
kecipak beningnya itu geram atau gerimis
sama-sama susah kita pahami
Tapi seseorang-- yang kemanapun kita berpindah
akan melulu berdiri di tengah-tengah
dengan lagak waskita menunjuk bergantian
atas
dan bawah, bawah dan atas, atas dan bawah
dan begitu terus sampai salah satu dari kita
ada
yang maju menampar mulutnya dan berseru
: kau saja yang ke neraka, heh--
Seekor anjing mengendus dan menjilat sekali dua
jempol kakimu yang berdarah. Ia memimpikan
seluruh perjalanan
milik kota ini berhenti dan mengumpulkan
diri
di koreng yang kekalbasah itu
Aku merangkak dan berdiri di tepian zebra cross
yang garis-garisnya sudah mangkak. Cuma untuk
menimbang-nimbang--seperti tabiat para pemikir--
apakah akan maju atau mundur atau bertahan atau menyerah
dengan melambaikan tangan di hadapan tiap orang
yang berhenti dan mendongak ke lampu merah
Gayam, 2017